Pernahkah anda belajar Sejarah tapi tidak dari jalur membaca atau diajari seseorang seperti guru, teman atau yang lain? Sebagai contoh tertarik karena adanya foto, melihat video, game atau bahkan mendengarkan podcast? Nah itu adalah contoh belajar Sejarah yang menggunakan pemahaman berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang memberikan layanan sesuai kebutuhan belajar murid, karena setiap murid punya minat, kemampuan, gaya belajar, dan latar belakang yang berbeda. Konteks dalam belajar Sejarah adalah seseorang dapat memanfaatkan minat pada objek tertentu untuk menarik minat belajar Sejarah. Pembelajaran berdiferensiasi dalam belajar Sejarah sangat penting untuk menumbuhkan minat belajar melalui berbagai macam cara tidak melulu melalui buku.
Pembelajaran Sejarah berdiferensiasi di kelas menjadi sangat penting ketika mengharuskan guru memberikan pemahaman kepada murid dengan minat, kemampuan, gaya belajar dan latar belakang murid yang berbeda beda dalam kelas Sejarah. Tantangan guru adalah bagaimana memahamkan murid yang memiliki karakteristik heterogen dalam kelas. Sebelum melaksanakan pembelajaran Sejarah, hendaknya seorang guru harus melakukan beberapa aktivitas agar pembelajaran sejarahnya dapat mengadaptasi pembelajaran berdiferensiasi.
Memahami Gaya Belajar Murid
Gaya belajar adalah cara khas seseorang dalam menerima, memproses, memahami, dan mengingat informasi. Setiap murid punya kecenderungan berbeda sehingga strategi guru juga perlu disesuaikan. Gaya belajar murid terbagi menjadi tiga yaitu auditori, kinestetik, dan visual.
Auditori
Ciri – ciri murid dengan gaya belajar auditori adalah murid mudah paham lewat penjelasan lisan, suka mendengarkan, hafal cepat lewat suara. Metode belajar yang efektif diantaranya ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, rekaman audio, lagu/puisi, mendengarkan podcast dan lain sebagainya. Dalam pembelajaran Sejarah bisa juga disuguhkan hal – hal yang berkaitan dengan pendengaran seperti rekaman pidato Bung Tomo, rekaman pembacaan teks Proklamasi, lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dibuat oleh W.R. Supratman dan lain sebagainya.
Kinestetik
Ciri murid dengan gaya belajar kinestetik adalah suka praktik langsung, bergerak, mencoba sendiri, sulit duduk diam lama. Strategi mengajar diantaranya roleplay, eksperimen, field trip, praktik laboratorium, membuat produk. Dalam pembelajaran Sejarah kita dapat memanfaatkan kegiatan yang memberikan sisi fisik dalam pembelajaran Sejarah seperti presentasi, bermain peran, menggambar peta Sejarah, membuat mindmap, kuis pembelajaran dan lain sebagainya.
Visual
Ciri murid dengan kecenderungan gaya belajar visual adalah lebih mudah paham lewat gambar, warna, diagram, peta, atau tulisan. Strategi mengajar dapat menggunakan slide/gambar, peta konsep, video, ilustrasi di papan tulis, poster. Dalam pembelajaran Sejarah kita dapat memanfaatkan media yang sifatnya visual sebagai alat bantu dalam belajar seperti slide presentasi, gambar, video, media fisik sumber Sejarah, peta, dan lain sebagainya.
Dalam satu kelas tentu memiliki porsi yang berbeda antara berapa persen auditori, kinestetik dan visual. Maka guru harus memahami bahwa lingkup ketiganya antara auditori, kinestetik dan visual setidaknya harus bisa terlingkupi dalam pembelajaran Sejarah. Tidak harus memiliki porsi yang sama, namun setidaknya terwakili dalam kegiatan pembelajaran Sejarah. Sebelum memahami berapa jumlah persentase gaya belajar di satu kelas, maka guru harus mengadakan survey guna memahami jumlah persentase gaya belajar menggunakan asesmen diagnostik non kognitif
Memahami Asesmen Diagnostik Non Kognitif dalam Pembelajaran Sejarah
Asesmen diagnostik non-kognitif adalah asesmen yang dilakukan guru untuk memahami kondisi siswa dari sisi non-akademik, yaitu hal-hal di luar pengetahuan materi. Aspek yang biasanya digali dalam asesmen diagnostik non-kognitif:
- Motivasi belajar (apakah siswa bersemangat atau tidak).
- Minat belajar (apakah suka pelajaran tertentu, misalnya sejarah, matematika, dll).
- Gaya belajar (visual, auditori, kinestetik).
- Kebiasaan belajar (belajar malam, belajar dengan musik, belajar kelompok).
- Kondisi emosional (sedang senang, cemas, lelah).
- Lingkungan belajar (dukungan orang tua, fasilitas belajar di rumah).
Bentuknya bisa berupa angket, survei singkat, atau pertanyaan reflektif sederhana yang dijawab siswa sebelum pembelajaran. Idealnya asesmen diagnostic non kognitif dilaksanakan oleh guru BK untuk selanjutnya dibeikan ke semua guru yang membutuhkan data tentang satu kelas. Dari hasil diagnostic non kognitif, guru dapat mempersiapkan metode atau cara mengajar yang paling efektif untuk kelas yang akan diajar.
Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi dalam Modul Ajar dan Pembelajaran
Dalam praktiknya, pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan melalui tiga aspek utama, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Pertama, diferensiasi konten berarti guru menyesuaikan materi dengan gaya belajar murid. Misalnya, bagi murid dengan kecenderungan visual, guru dapat menyiapkan artikel, gambar, peta, atau video dokumenter. Untuk murid auditori, materi dapat diberikan dalam bentuk rekaman pidato sejarah, podcast, atau penjelasan lisan. Sementara bagi murid kinestetik, konten dapat diperkaya dengan aktivitas praktik seperti roleplay atau simulasi. Kedua, diferensiasi proses menekankan pada cara murid mempelajari materi. Murid dapat belajar melalui diskusi kelompok, presentasi kelas, proyek penelitian kecil, atau bahkan permainan peran. Dengan proses yang bervariasi, setiap murid dapat menemukan cara belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. Ketiga, diferensiasi produk berkaitan dengan hasil belajar yang diharapkan dari murid. Produk ini tidak harus seragam, tetapi bisa disesuaikan dengan minat dan gaya belajar murid. Misalnya, ada kelompok yang menghasilkan poster atau peta konsep, sementara kelompok lain membuat presentasi, esai, atau bahkan video pendek yang menjelaskan peristiwa sejarah tertentu.
Peran Guru dalam Pembelajaran Sejarah
Guru dalam pembelajaran sejarah tidak lagi diposisikan sebagai satu-satunya sumber informasi, melainkan sebagai fasilitator yang mampu mengakomodasi kebutuhan belajar siswa. Artinya, guru perlu memahami bahwa setiap murid memiliki cara berbeda dalam menerima dan mengolah informasi, sehingga peran guru adalah menyediakan berbagai pilihan cara belajar agar semua murid bisa terlayani.
Selain itu, guru juga menjadi penghubung antara minat siswa dengan materi sejarah. Misalnya, siswa yang memiliki ketertarikan pada musik bisa diajak memahami sejarah melalui lagu perjuangan, sementara yang tertarik dengan teknologi bisa diajak menelusuri arsip digital atau peta interaktif. Dengan begitu, sejarah tidak dipandang kaku, tetapi relevan dengan dunia murid.
Guru juga berperan memberikan ruang kreativitas bagi murid, misalnya melalui proyek, pameran, atau simulasi peristiwa sejarah. Namun pada saat yang sama, guru tetap memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai. Kreativitas tidak boleh hanya sekadar kegiatan, tetapi harus mengarahkan siswa untuk memahami konsep, nilai, dan makna yang terkandung dalam sejarah.
Dengan peran yang fleksibel ini, guru menjadi jembatan antara masa lalu yang dipelajari dalam sejarah dengan kebutuhan masa kini yang dialami murid.
Tantangan & Solusi
Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas sejarah, tentu ada beberapa tantangan yang dihadapi guru. Salah satunya adalah keterbatasan waktu. Sering kali, guru dituntut menyelesaikan target kurikulum dalam waktu yang terbatas sehingga sulit memberi ruang variasi strategi. Selain itu, adanya banyak variasi murid dengan gaya belajar, minat, dan kemampuan yang berbeda juga membuat guru harus lebih cermat dalam menyiapkan skenario pembelajaran. Tidak kalah penting, kesiapan guru sendiri dalam menguasai metode maupun media pembelajaran bisa menjadi kendala tersendiri.
Namun, setiap tantangan tentu ada solusinya. Guru dapat memanfaatkan media sederhana yang dekat dengan kehidupan siswa, seperti gambar, lagu, atau cerita sejarah lokal, tanpa harus menyiapkan perangkat yang rumit. Kolaborasi dengan guru lain, khususnya guru BK, juga dapat membantu dalam memahami kondisi non-kognitif siswa sehingga pembelajaran bisa lebih tepat sasaran. Selain itu, teknologi dapat menjadi penopang penting: guru bisa menggunakan video pendek, QR code berisi materi tambahan, hingga kuis online interaktif untuk membuat kelas lebih hidup.
Dengan cara ini, kendala waktu, variasi murid, dan keterbatasan guru bukan menjadi hambatan, melainkan tantangan yang bisa diatasi dengan kreativitas dan kerjasama.
Harapan Akhir
Melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi, diharapkan proses belajar sejarah menjadi lebih bermakna bagi siswa. Sejarah tidak lagi dipandang sebagai kumpulan fakta yang harus dihafalkan, melainkan pengalaman belajar yang mampu menyentuh minat dan gaya belajar mereka. Dengan demikian, setiap siswa dapat menemukan cara terbaik untuk memahami perjalanan masa lalu bangsanya.
Pada akhirnya, keberagaman gaya belajar bukan menjadi kendala, tetapi justru kekuatan yang bisa dimanfaatkan guru untuk menghadirkan suasana kelas yang lebih hidup, interaktif, dan relevan. Harapannya, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan sejarah, tetapi juga merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mereka masing-masing.
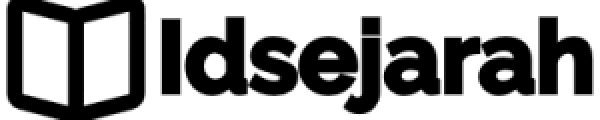









Leave a Comment